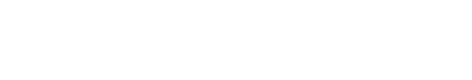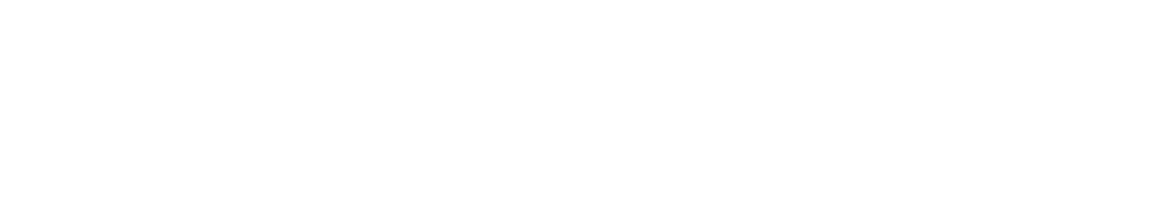Dunia berpacu dengan waktu. Aktivitas manusia mulai dari produksi polusi hingga populasi yang kian membludak telah membawa perubahan terhadap iklim di muka bumi yang secara fundamental telah mengubah tatanan dunia yang semakin dekat dengan kepunahan peradaban umat manusia. Aufklarung, peristiwa agung di tataran tanah Eropa yang dikenal dengan masa pencerahan ternyata merupakan awal dari segala malapetaka di muka bumi yang tengah kita hadapi saat ini. Siapa sangka, revolusi industri yang telah mengantarkan dunia dan seisinya pada puncak kejayaan ekonomi dan ilmu pengetahuan, justru semakin mendekatkan bumi pada peradaban terakhirnya. Lantas, apa sebetulnya yang dimaksud dengan perubahan iklim, si “pembawa malapetaka” itu? Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengemukakan bahwasanya “Perubahan iklim merupakan suatu peristiwa dimana muka bumi mengalami perubahan suhu dan pola cuaca berkepanjangan. Aktivitas manusia dalam hal pembakaran bahan bakar fosil melalui minyak, batu bara, dan gas alam yang mengakibatkan emisi gas rumah kaca menjebak panas matahari di bumi sehingga berimplikasi pada naiknya suhu bumi”. Sebuah studi dari NASA’s Goddard Institute for Space Studies (GISS) menemukan fakta mengejutkan bahwa sejak revolusi industri dijalankan, planet kita telah mengalami peningkatan suhu dengan rata-rata 1.1-1.3 derajat celcius sejak tahun 1880. Bahkan, National Aeronautics and Space Administration (NASA) melalui studinya menemukan fakta mencengangkan bahwa tahun 2020 menjadi tahun terpanas dalam sejarah peradaban manusia. Namun, sebagian dari kita tidak banyak yang menyadari hal itu tentunya, sebagian dari kita justru masih asik makan daging tanpa tahu semasif apa dampaknya bagi lingkungan. Tahun 2020 menjadi mengerikan bagi bumi ketika dihadapkan pada kenyataan terjadinya peristiwa kebakaran hutan besar-besaran di daratan hutan Australia, dimana api melahap 46 juta hektar lahan yang asap dan partikelnya bahkan berhasil mencapai ketinggian 18 mil di atmosfer. Selain peristiwa yang terjadi di Australia, iklim periodik La Nina dan El Nino juga turut memperparah kondisi iklim muka bumi di tahun 2020. Cuaca ekstrem yang mengakibatkan banjir bandang dan angin topan, kekeringan yang secara dramatis menghilangkan pasokan air bersih yang berujung pada kelaparan masal telah terjadi di berbagai belahan dunia, bukan hanya sekedar dongeng semata. The Economist memprediksi bahwa iklim bumi akan mengalami peningkatan sebanyak 3 derajat celcius diakhir abad ke-21. Dimana suhu global yang meningkat akibat perubahan iklim akan berimplikasi pada mencairnya lapisan es di kutub. Jika lapisan es di kutub naik, maka hal tersebut akan membuat permukaan laut menjadi naik. Permukaan laut yang naik akan secara langsung mengakibatkan banyak kota-kota metropolitan di dunia tenggelam tak tersisa seperti Kota Mumbai di India, Kota Osaka di Jepang, termasuk Kota Jakarta, ibu kota negara tercinta kita. Breakthrough National Centre for Climate Restoration mengemukakan skenario terburuk yang menyatakan bahwa pada tahun 2050, manusia diprediksi tidak mampu lagi untuk bertahan hidup di bumi akibat perubahan iklim yang sudah tidak terkendali. Di tengah masifnya dampak yang diproyeksikan oleh para ilmuwan, mari kita sejenak menakar dan menelusuri sejauhmana pemerintah Indonesia telah bertindak. Pemerintah Indonesia sendiri sebetulnya telah menyadari keniscayaan isu perubahan iklim beserta dampak masifnya bagi keseimbangan ekologi nasional, bahkan global. Pada tahun 2016, Pemerintah Indonesia turut meratifikasi perjanjian skala global, yaitu Conference of the Parties (COP) 21 yang dihelat di Paris, Prancis yang dikenal dengan nama Paris Agreement yang menekankan komitmen seluruh negara peserta untuk melakukan reduksi karbon dan menahan laju kenaikan suhu rata-rata di muka bumi agar tidak sampai ada di angka 2 derajat celcius diakhir abad ke- 21. Tidak sampai disitu, Pemerintah Indonesia kembali mengikuti COP 26 yang dihelat di Glasgow, Skotlandia pada tahun 2021 sebagai tindak lanjut dari COP 21.
Pada COP 26, Indonesia turut meratifikasi perjanjian ini dengan memberikan komitmen penuh untuk dapat mencapai emisi 0 pada tahun 2050 dengan pengurangan signifikan pada tahun 2030 melalui komitmen untuk menghapus batu bara, kendaraan berbahan bakar minyak, dan bersedia memberikan janjinya untuk melindungi hutan. Jika ditinjau dari dua perjanjian iklim dunia terakhir tersebut, Pemerintah Indonesia tak segan menyatakan keseriusannya dalam memerangi isu perubahan iklim. Namun, bagaimana dengan realitanya? Pemerintah Indonesia saat ini tengah dalam pembahasan terkait Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT) sebagai langkah awal untuk merealisasikan komitmennya pada perjanjian COP 21 dan 26. Sekilas memang Pemerintah Indonesia terkesan cepat dan tanggap dalam hal ini. Namun, permasalahan muncul ketika publik menemukan dua isu krusial yang terkandung dalam RUU EBT. Pertama, di dalam RUU EBT ini terlihat keinginan Pemerintah Indonesia terkait pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), dimana energi nuklir akan berperan sebagai objek transisi energi yang digadanggadang akan menjadi tumpuan Indonesia kedepan. Bukan tanpa alasan, keseriusan tersebut secara gamblang disebutkan pada RUU EBT ini dimana termuat pembahasan terkait penggunaan energi nuklir mulai dari perizinan usaha, fungsi kelembagaan, monitoring, hingga optimalisasi energi nuklir. Tidak sampai disitu, dalam RUU EBT ini juga memuat konfigurasi terkait Majelis Pertimbangan Pembangkit Daya Nuklir yang katanya akan bertugas sebagai perancang dan perumus strategi dan arah kebijakan nasional berkenaan pembangkit daya nuklir lengkap dengan penyediaan tempat penyimpanan lestari limbah radioaktif tingkat tinggi. Hal yang menambah kegeraman publik ialah dalam RUU EBT ini, pemerintah tidak mengungkapkan rasionalisasi logis terkait penggunaan energi nuklir sebagai energi baru. Perbincangan pemerintah terkait energi nuklir sebetulnya memang sudah ada sejak lama, dalam Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional dikemukakan bahwa “Energi nuklir akan digunakan sebagai opsi terakhir dengan syarat pemerintah harus menujukan perhatiannya secara penuh pada faktor keselamatan yang ketat. Dengan catatan, pemerintah harus mendahulukan optimalisasi energi baru dan terbarukan”. Namun, data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan fakta bahwa nyatanya upaya optimalisasi potensi energi baru dan terbarukan Indonesia hingga saat ini baru berada di kisaran angka 1,85 persen. Dari sini, timbul pertanyaan terkait seberapa relevan pengunaan energi nuklir yang notabennya adalah opsi terakhir, di tengah belum optimalnya upaya optimalisasi dari potensi energi baru dan terbarukan Indonesia yang melimpah? Sekali lagi, pembicaraan terkait penggunaan energi nuklir di Indonesia sebetulnya bukan hal yang baru, sudah sejak lama Pemerintah Indonesia mulai memikirkan opsi penggunaan energi nuklir di Indonesia. Meskipun demikian, publik sebagian besar selalu menentang wacana ini ketika kembali menyeruak. Bukan tanpa alasan, sekarang marilah kita pahami dan analisis terkait penggunaan energi nuklir di Indonesia. Sebagaimana kita sama-sama ketahui, energi nuklir termasuk ke dalam jajaran pembangkit listrik berskala besar. Namun, tentunya kita sama-sama tahu pula seberapa besar resiko yang dapat terjadi dari penggunaan energi nuklir ini. Mari kita berkilas balik, rasanya publik di dunia masih ingat betul terkait tragedi meledaknya reaktor PLTN Chernobyl di Ukraina yang terjadi pada tahun 1986 silam. Tragedi ini dikenang sebagai sejarah kelam dunia terkait malfungsi energi nuklir. Tak tanggungtanggung, tragedi ini telah melepaskan radioaktif 400 kali lebih banyak dari pada nuklir yang digunakan pada bom Hiroshima, tahun 1945 silam. Dampaknya, 100.000 km persegi wilayah dinyatakan terkontaminasi radioaktif, 4000 orang tewas baik secara langsung maupun tidak langsung dan yang masih hidup pun tidak lantas selamat begitu saja, mereka akhirnya harus menelan pil pahit untuk hidup dengan cacat tubuh dan kanker yang menggerogoti tubuh. Hal yang lebih mengerikan adalah, Chernobyl saat ini menjadi kota mati yang tak menyisakan penghuni, yang tersisa hanyalah sisa-sisa bencana lengkap dengan radiasi nan mengerikan yang telah membaur di udara. Usut punya usut, ternyata berbagai penelitian yang diadakan oleh para ilumuwan dunia menemukan fakta bahwa negara-negara dunia kian meninggalkan penggunaan tenaga nuklir. Data empiris menunjukkan bahwa terus terjadi penurunan terhadap persentase listrik dunia yang bersumber dari PLTN yang didasarkan atas analisis Schneider dan Froggat yang menunjukkan bahwa persentase listrik dunia yang berasal dari PLTN telah turun dari 17% pada tahun 1996 menjadi 10,5% pada tahun 2018. Sehingga, relevansi peggunaan energi nuklir di Indonesia pun menjadi pertanyaan. Untuk apa Indonesia menggunakan energi nuklir disaat negara-negara lain meninggalkannya? Namun, bukan hal yang mengejutkan sebetulnya, karena sejatinya negara tercinta kita memang selalu begitu, selalu tertinggal satu langkah dibanding negara lain di dunia ini.
Di samping itu, pemerintah seharusnya tahu betul seperti apa kondisi geografis Indonesia yang berada di kawasan ring of fire. Gempa bumi, gunung melestus, bahkan tsunami adalah sederet bencana yang menjadi langganan terjadi di Indonesia. Dari sini, timbul pertanyaan seberapa jauh persiapan yang telah dilakukan oleh pihak pemerintah untuk memitigasi segala resiko buruk yang mungkin terjadi jika kekeuh pada pendiriannya untuk membangun PLTN di Indonesia. Apalagi, dana yang dibutuhkan untuk membangun PLTN tidaklah sedikit. Dilansir dari Liputan6.com, butuh dana sekitar Rp. 70 triliun untuk membangun PLTN di Indonesia. Di tengah pandemi yang belum usai, utang luar negeri Indonesia meroket hingga mencapai angka Rp. 5.948 triliun, dari mana dana untuk membangun PLTN dapat muncul? Sementara untuk membayar utang luar negeri saja Pemerintah Indonesia sudah cukup bingung untuk mengefisiensikan APBN dengan memotong anggaran kesana kemari. Belum lagi apabila kita mengingat budaya korupsi yang masih mandarah daging di tubuh birokrasi Indonesia, permasalahannya menjadi lebih pelik lagi. Oleh karenanya, rasanya PLTN bukanlah suatu jawaban shahih yang dapat dijustifikasi sebagai pengganti energi fosil di Indonesia. Mengingat berbagai keterbatasan Indonesia dalam pengembangan sumber daya nuklir nasional dengan berbagai resiko yang ada, maka opsi ini dinilai sangatlah tidak bijak bagi Indonesia. Isu krusial kedua yang termaktub dalam RUU EBT ini ialah terkait masih digunakannya batu bara yang tinggi emisi. Hal yang sangat mengherankan dan menggelitik tentunya. Hadir dengan mengemban nama energi terbarukan, namun justru siapa sangka nyatanya pembahasan RUU ini masih berkutat pada penggunaan batu bara, dan kita tahu betul tentunya bahwa batu bara jelas bukan energi terbarukan. Sehingga kehadiran RUU ini pun akhirnya dinilai publik hadir tanpa menjawab permasalahan aktual yang ada untuk menekan penggunaan energi fosil di Indonesia. Bukan tanpa alasan, pengaminan atas tudingan masyarakat tersebut terlihat dari fakta di lapangan. Dilansir dari Liputan6.com, data pada tahun 2021 menunjukkan bahwa Indonesia masih aktif menggunakan energi fosil dengan jenis batu bara hingga mencapai angka 88 persen. Bukan angka yang menggembirakan tentunya, padahal pemerintah tahu betul bahwa penggunaan energi fosil merupakan biang keladi utama sebagai penyumbang emisi terbesar. Sehingga disini, patut dipertanyakan komitmen Pemerintah Indonesia atas dua perjanjian iklim dunia yang telah diratifikasinya untuk mengurangi penggunaan energi fosil. Dimana sebetulnya letak integritas Pemerintah Indonesia? Publik geram tentunya, sebab dalam hal ini pemerintah ternyata masih belum mendapatkan solusi konkret yang aplikatif untuk memerangi krisis iklim dunia yang sudah di depan mata.
Laju perubahan iklim di Indonesia sebetulnya saat ini masih bisa tertahan karena hutan Indonesia yang masih luas sehingga karbon masih bisa diserap oleh pohon di hutan. Forest Watch Indonesia (FWI) mengemukakan fakta bahwa hutan Indonesia menempati urutan ketiga dalam daftar hutan terluas di dunia setelah Brazil dan Republik Kongo, sehingga hutan Indonesia dianggap sebagai salah satu paru-paru dunia. Namun hal tersebut tak lantas membuat kita bisa bernafas lega. Karena nyatanya kini kekhawatiran global memuncak ketika ternyata hutan Indonesia terus mengalami laju deforestasi yang tinggi setiap tahunnya, yaitu sekitar 2 juta hektar per tahun yang disebabkan oleh alih fungsi lahan hutan. Pemerintah Indonesia sebetulnya telah mencoba menekan laju deforestasi melalui implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengupayakan kelestarian hutan Indonesia melalui perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan serta penegakan hukum. Namun kesigapan Pemerintah Indonesia melalui upaya tersebut menjadi tidak relevan ketika nyatanya Pemerintah Indonesia masih terus memberikan izin pembukaan lahan baru di hutan Indonesia yang notabennya adalah paru-paru dunia. Pengaminan atas isu tersebut terlihat dari masih masifnya konversi lahan hutan di Indonesia menjadi perkebunan dengan tanaman komersil seperti kelapa sawit. National Geographic mengemukakan bahwa dalam beberapa dekade terakhir, kawasan hutan di Indonesia khususnya di Pulau Sumatra masif dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit. Saat ini, dampak masif dari konversi lahan hutan tersebut telah terasa. Bukan hanya spekulasi semata, Tim Peneliti Internasional dari University of Gottingen Jerman menemukan fakta bahwa ekspansi perkebunan kelapa sawit tersebut telah membuat suhu di wilayah Indonesia bagian Sumatra menjadi lebih panas. Saya rasa pemerintah seharusnya sudah tahu betul bahwa hal seperti ini akan terjadi. Namun mengapa pembukaan lahan baru di lahan hutan tersebut tetap diizinkan? Maka sekali lagi, disini telihat inkonsistensi Pemerintah Indonesia dengan komitmen yang telah digemborkannya, seluruhnya masih “utopis” ternyata. Hal ini seolah menjustifikasi anggapan publik bahwa beragam regulasi yang dikeluarkan hanya sekedar pencitraan saja untuk menyelamatkan wajah Pemerintah Indonesia dari seruan publik dan dunia internasional. Nampaknya, untuk dapat mencapai emisi 0 pada tahun 2050 dengan pengurangan signifikan pada tahun 2030 masih menjadi hal yang “utopis” bagi Indonesia. Apa harus menunggu Jakarta tenggelam dulu untuk bisa serius dalam menangani isu ini? Kita tidak butuh tanggapan, tidak butuh sanggahan, apalagi janji manis dengan segala omomg kosongnya. Aksi nyata yang mampu menghasilkan dampak yang masif dan berkelanjutan adalah yang kita sama-sama butuhkan saat ini. Kita butuh keseriusan pemerintah dalam menangani isu perubahan iklim ini, bukan hanya sekedar harapan palsu saja. Pemerintah Indonesia harus segera mengambil langkah strategis dengan penuh keseriusan. Seluruh departemen maupun badan di Indonesia harus aktif mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan climate action di seluruh lini pemerintahan dan seluruhnya wajib untuk membuktikan kemajuan yang nyata, bukan angan-angan. Sebab, responsibilitas perubahan iklim tidak berpusat pada satu departemen maupun badan saja, semua harus terlibat dan bergerak aktif.
Sekali lagi, permasalahan perubahan iklim merupakan permasalahan pelik dengan skala global. Maka dari itu, tentunya publik harus dilibatkan dalam segala prosesnya, mulai dari diskusi hingga aksi nyata dalam upaya reduksi emisi karbon. Sebab, jelas pemerintah tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan ini sendirian. Agaknya Pemerintah Indonesia harus mencoba untuk menggunakan strategi collaborative governance dalam upaya menyelesaikan masalah ini dengan melibatkan lima unsur pentahelix, yang terdiri dari pemerintah sendiri, akademisi, sektor swasta atau bisnis, komunitas terkait, dan media. Karena sejatinya, permasalahan perubahan iklim adalah permasalahan setiap orang yang hidup di bumi, maka seluruhnya harus mengambil peran dan tindakan dengan saling bergandengan tangan dan mengesampingkan egosentris pribadi maupun golongan. Kemudian, Pemerintah perlu mengeluarkan dan mengaplikasikan kebijakan yang memang menggambarkan visi jangka panjang dengan mempertimbangkan relevansinya terhadap rakyat, seperti pemotongan harga atau bahkan pembebasan biaya transportasi umum yang dapat memacu masyarakat untuk menggunakan transportasi umum, sehingga laju emisi karbon yang dihasilkan oleh kendaraan pribadi masyarakat pun dapat berkurang drastis. Pemerintah juga dapat mulai memberi perhatian lebih dan mensosialisasikan green jobs kepada publik. Apa itu green jobs? Green jobs merupakan istilah yang dikeluarkan oleh organisasi buruh dunia (ILO) yang mengacu pada jenis pekerjaan ramah lingkungan untuk agenda pembangunan berkelanjutan dan rendah emisi. Disamping itu, pemerintah perlu menunjukkan integritasnya terkait komitmen untuk dapat melakukan peralihan bahan bakar fosil menuju energi yang lebih ramah lingkungan yang memang aplikatif untuk diimplementasikan di negeri kita, baik melalui optimalisasi penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) maupun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
Dalam pembicaraan isu perubahan iklim ini, generasi Z memang selalu menjadi yang paling vokal. Bukan tanpa alasan, ketika masa dari kaum baby boomer, generasi X dan Y telah habis, tentunya bumi ini akan diwariskan kepada kami. Wajar saja jika kami memiliki kepedulian lebih atas isu ini. Karena jelas, kami yang akan menanggung getahnya. Perubahan iklim merupakan keadaan darurat global. Maka dari itu, sudah barang pasti kami menginginkan para pemangku kepentingan di Indonesia untuk membuat kebijakan yang sebijak-bijaknya guna mengatasi permasalahan ini. Tentunya, yang kami harapkan bukan hanya kebijakan yang sekedar hadir saja, tapi kita semua butuh kebijakan jangka panjang yang memang adaptif dan aplikatif yang berisi seluruh komitmen Pemerintah Indonesia yang berintegritas, tidak “utopis”. Kita tentunya tak bisa tinggal diam ketika melihat orang-orang menderita dan sekarat di tengah alam yang menuju pada kehancurannya. Para pemangku kebijakan harus sadar bahwa saat ini dunia berada di awal kepunahan massal. Berhenti membicarakan negara mana yang paling berkuasa, entah dari bidang ekonomi, militer, ataupun lainnya. Saat ini kita punya permasalahan kompleks yang mempertaruhkan masa depan peradaban umat manusia. Maka cukuplah kalian membicarakan uang dan seluruh angan-angan tentang pertumbuhan ekonomi yang kekal. Sekarang mari kita bergandengan tangan untuk menyelamatkan planet kita, bumi kita tercinta.
Oleh:
Destiani Putri Utami
(Mahasiswa Angkatan 2018)